Merantau Bagian Tiga
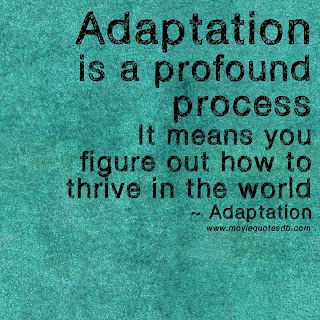 |
| Image source: here |
Di salah satu akun jejaring sosial
pribadi saya tertulis “sesuatu yang bergerak dan tidak menetap” sebagai
gambaran singkat profil saya. Ini bermula di satu waktu saat saya menyadari
bahwa setiap tahun saya selalu berpindah tempat tinggal, baik kos-kosan atau
kota. Entah mengapa, pada waktu itu juga saya memiliki firasat kalau sepertinya
dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan pola hidup seperti ini masih akan
terus saya jalani. Pede berlebihan memang, tapi nyatanya, toh, saya belum bisa
membayangkan kehidupan menetap dalam jangka waktu lama di sebuah kota. Dan
ternyata itu berlangsung hingga kini.
Bulan ini, tepatnya Juli 2013,
bisa dibilang saya sudah sebulan menetap di Makassar. Keputusan ini sebenarnya
terbilang instan. Fase pernikahan adalah yang membawa saya ke sini, walau
sebetulnya, saya dan suami tadinya berencana untuk menetap di Jakarta setelah
menikah. Rencana tinggal rencana dan inilah yang menjadi kesepatakan bersama
serta keputusan terbaik untuk berdua. Maka jadilah Makassar sebagai kota
keempat yang menjadi tempat tinggal saya selama 25 nyaris 26 tahun ini hidup.
Soal merantau memang bukan
merupakan hal baru bagi saya. Merantau sendiri, bukan karena kewajiban
orangtua. Selepas lulus SMA, tepatnya saat usia saya masih menuju 18 tahun,
saya menyeberangi Laut Jawa dari Balikpapan menuju Bandung (geser sedikit ke
Jatinangor) untuk menempuh studi perguruan tinggi. Lima tahun menetap di sana,
saya lanjut pindah ke Jakarta untuk bekerja dan menetap di sana selama dua
tahun hingga akhirnya saya menikah di akhir Mei lalu dan pindah ke sini.
Walaupun pola berpindah sama, yaitu packing
sekaligus memilih dan memilah mana barang yang layak dibawa dan mana barang
yang harus ditinggalkan, perantauan kali ini terasa beda.
Begini bedanya. Saat saya pindah
ke Bandung lalu Jakarta, fase itu bisa dibilang sudah ada dalam prosedur
kehidupan seorang anak, yaitu mengejar pendidikan dan setelah usai, iapun harus
mengejar peruntungan nasib. Ada yang menanti dan dinanti, ada alasan yang
mewajibkan pindah. Kali ini, pindah karena menikah adalah pilihan. Posisinya adalah
saya sebagai seorang istri yang memilih setuju untuk pindah ke kota dimana
suami saya menetap sementara. Saya bisa memutuskan tetap di Jakarta dan masih
menjalani pekerjaan saya di sana, tapi pilihan saya adalah ini. Artinya, saya
pindah ke sini bukan karena ada alasan yang mewajibkan, bukan karena ada yang
menanti dan dinanti. Kehidupan rumah tangga sudah jelas menanti dan dinanti
semenjak kami berdua mengucap janji pernikahan. Dan walaupun saya memutuskan
untuk tetap di ibukota, toh, predikat saya sudah bertambah menjadi seorang
istri dan ibu rumah tangga. Tapi, berhubung saya pindah ke sini sebagai wujud
pilihan atas predikat yang sudah bertambah itu, maka sayalah yang harus mencari
sesuatu yang menanti dan dinanti itu. Ya, ini juga menjadi pembeda fase merantau saya dari yang sudah-sudah. Saya merantau tidak lagi sendiri, tapi berdua, sepasang. Namun sebagai seorang pribadi, saya tetap menjadi pihak yang harus menciptakan alasan atas
pilihan saya tadi, karena saya tidak lagi disodorkan oleh kewajiban berprosedur
yang harus saya hadiri, seperti: perkuliahan atau kerja. Tidak ada sistem “wajib”
tadi. Menjadi ibu rumah tangga itu otomatis, karena saya sekarang sudah menikah
dan menjadi istri orang. Walaupun saya (misalnya) kembali bekerja kantoran, toh, saya tetap
menjadi ibu rumah tangga. Namun, inilah tantangan berikutnya dari perantauan
saya kali ini: memilih prosedur sebagai alasan saya merantau ke sini. Beda
dengan sebelumnya dimana saya pindah karena sudah wajib menjalani sesuatu yang
menanti dan dinanti itu.
Di sini, saya harus belajar
sendiri beradaptasi. Suami saya jelas membantu dengan pengetahuan yang ia
miliki. Tapi terlepas dari itu semua, saya harus mencari celah sendiri untuk
menemukan pola hidup yang harus dijalani selama enam bulan ke depan. Semuanya
tidak lagi berjalan serba “otomatis”. Itulah yang membuat fase kali ini lebih
sulit dari dua fase merantau sebelumnya. Kami tidak punya keluarga yang bisa
membimbing ini itu, tapi kami harus menciptakan pengalaman sendiri untuk
menjadi “tahu” dan berhasil menjadi warga kota ini seperti orang lain. Proses
ini memang lebih lambat untuk dijalani dan dikuasai, tapi bagi saya ini jelas
menjadi tantangan baru yang tidak bisa saya pelajari dari orang lain, melainkan
dari dan dengan diri sendiri. Ya, pengalaman kali ini harus saya kreasikan dan
lukis sendiri. Sulit? Pasti. Tapi menyenangkan karena saya tidak punya contoh
dan orang yang mendikte seperti apa semestinya. Kami jauh dari keluarga dan kerabat,
dan harus belajar memutuskan segala sesuatu berdua. Di luar itu, saya juga
harus belajar untuk menciptakan pengalaman bagi kapal kecil kami ini agar bisa
menjadi luwes untuk hidup di kota orang. Meskipun tak sedikit yang heran soal
kepindahan saya dari ibukota ke “daerah”, tapi saya merasa beruntung. Merantau ke
ibukota di negeri ini sudah menjadi pola “wajar” dan nyaris “wajib” bagi
siapapun yang hendak menyusun simpul-simpul hidupnya atas nama kemapanan.
Peluang banyak tercipta di sana. Bahkan saya juga berpikir bahwa suatu hari
nanti kami bisa dengan mudah kembali ke ibukota. Tapi kesempatan untuk tinggal
di salah satu kota asing di Indonesia yang tidak memiliki “alasan” untuk saya
datangi, tentu jarang. Dan satu hal lagi, adaptasi ke sebuah kota yang tidak
memiliki segalanya seperti Jakarta bukanlah perkara mudah. Di sinilah letak
kesenangan menjalani tantangan itu terhampar. Dan ini juga menjadi salah satu
proses mengamini bio singkat saya di atas. Selalu bergerak dan tidak menetap,
hingga tiba waktunya saya dan dia harus benar-benar menetap. Haruskah? Tidak
tahu.
Selamat menciptakan pengalaman!
Makassar, 02 Juli 2013



Comments
Post a Comment